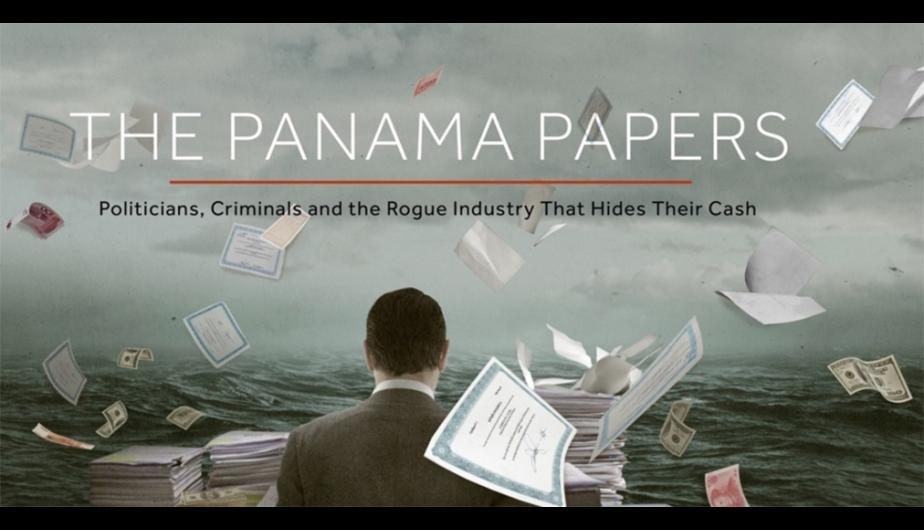Masalah ustadz Solmed vs BMI Hongkong masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan di media. Tadi siang saja di saat makan siang, saya lihat di televisi swasta, acara yang biasanya membahas gosip siang itu membahas masalah kasus itu. Permasalahan ini kalau mau ditelusuri akar masalahnya bisa melebar ke arah yang paling fundamental, yaitu tidak adanya standarisasi profesi da’i dan aktivitas berdakwah.
Pertama, sebelum membahas itu, mari luruskan satu hal dulu. Menyamakan persepsi, yaitu dalam masalah Istilah “Ustadz/Ustadzah“. Ustadz dalam bahasa Arab artinya “Guru”. Dengannya jika melihat secara etimologi ini siapapun guru, mengajar bidang apapun, itu ustadz.
Namun, di Indonesia kata ustadz ini mengalami penyempitan makna, yaitu hanya pada guru ngaji atau orang yang mengajarkan agama. Selain itu, kata ustadz ini pun sudah mengalami pensakralan makna. Dikarenakan ustadz itu identik dengan agama maka stigma yang muncul di masyarakat kita menjadi tabu ketika mengkritik ustadz. Takutkwalat. Karena agama itu sendiri sudah sakral, maka orang yang membawanya pun terbawa sakral.
Kedua, istilah “Da’i”. Kata ini diambil dari kata dasar “Da’a – Yad’u” yang artinya “mengajak”. Dengan demikian, aktivitas mengajak orang lain menuju jalan Allah Swt disebut “Da’wah” dan orangnya disebut “Da’i“.
Kata da’i dan ustadz maknanya berhimpitan. Da’i itu sering disebut ustadz tapi belum tentu ustadz itu seorang da’i. Kata ustadz lebih umum dibanding kata da’i. Guru ngaji misalnya itu disebut juga ustadz tapi dia bukan da’i.
Da’i di sini pun maknanya sudah berbelok. Jika mengacu pada arti katanya, ustadz juga seharusnya da’i karena dia mengajak pada kebenaran. Mengajarkan nilai-nilai agama. Tapi, da’i konotasinya bermakna “Penceramah”: orang yang melakukan aktivitas dakwah di mimbar-mimbar, di atas podium atau panggung, dengan kelihaiannya dari aspek retorika dan penguasaan terhadap ajaran-ajaran agama. Ini arti da’i.
Ketiga, ada lagi istilah lain yang serupa, yaitu muballigh. Berasal dari kata “Ballagha – Yuballighu” yang artinya “menyampaikan”. Aktivitasnya disebut “Tabligh” dan orangnya disebut Muballigh. Kata ini maknanya mirip dengan dakwah tapi berbeda cakupan. Tabligh maknanya lebih umum dari dakwah. Siapa saja orang Muslim harus menjadi muballigh, didasarkan pada hadits, “Ballighu ‘anni wa law ayyat“..”Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat”. Dengannya untuk menjadi muballigh (menyampaikan pemahaman dirinya terhadap orang lain mengenai nilai-nilai agama) itu bukan profesi melainkan kewajiban.
Adapun dakwah itu lebih khusus maknanya. Kenapa pendakwah (da’i) itu lebih khusus? Karena dituntut profesionalitas. Dari mana landasannya? Yaitu QS Ali-Imran: 104: “Wal takun minkum ummatun yad’una ila al-khair ya’muruna bil ma’ruf wa yanhauna ‘an al-munkar” (Hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemunkaran).
Kata “Minkum” pada ayat itu adalah landasannya. Minkum artinya “di antara kalian”..apa konsekuensi arti kata ini? Ini berarti terbatas, khusus, atau dalam istilah lain wajibnya adalah wajib kifayah, kewajibannya bukan untuk setiap orang melainkan orang-orang tertentu saja. Kata minkum dalam ayat itu pun mengandung makna bahwa dakwah itu harus profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Beda dengan kata tabligh di atas. Nah, di sini permasalahan utamanya.
Masalahnya yaitu dakwah seringkali bercampur dengan tabligh. Adakalanya orang yang mendakwahkan nilai-nilai agama bukan dari kalangan yang benar-benar mengerti seluk-beluk agama, tapi orang yang justru mungkin hanya mengerti sedikit tentang agama. Dan, ia menyebutnya sebagai “dakwah” padahal itu bukan dakwah. Terjadilah degradasi makna dakwah dan yang paling utama degradasi standarisasi pendakwah. Ketika agama disampaikan oleh orang yang sembarangan tentu akan berbeda dengan orang yang memang menguasainya. Profesionalitas bukan saja harus ada di bidang bisnis melainkan juga di bidang agama.
Dengan kata lain dakwah itu bidang profesi yang tidak bisa dilakukan oleh yang bukan ahlinya. Karena ia profesi seharusnya ada standarisasi profesi atau kualifikasi pendakwah. Siapa saja yang berhak berdakwah dan siapa saja yang tidak. Tanpa menghilangkan aktivitas tabligh. Tabligh sifatnya lebih ke personal dan dakwah lebih ke cakupan sosial yang lebih luas. Silahkan saja setiap orang bertabligh tapi ketika sudah masuk ranah publik itu dakwah namanya. Dia harus punya kualifikasi dan memang orang yang kompeten dalam hal itu. Standarisasi ini bisa saja dalam bentuk sertifikasi atau surat keputusan dari suatu lembaga terpercaya yang dipilih umat untuk melakukan itu. Dai itu kaitannya dengan umat yang jumlahnya jutaan maka harus diatur. Bukan berarti juga setiap mahasiswa yang lulus jurusan dakwah berhak untuk menjadi da’i. Belum tentu.
Ini sangat penting, karena agama terdegradasi, terdevaluasi nilai dan kandungannya justru dari aktivitas yang-katanya-dakwah. Padahal mungkin hanya orang yang mengerti sedikit tentang agama tapi sudah berani mengklaim memiliki kunci surga. Ini fenomena yang terjadi.
Kasus Ustadz Solmed ini adalah salah satu akibat dari fenomena itu, yaitu tidak adanya standarisasi dalam berdakwah: harus seperti apa dan bagaimana kode etik dalam berdakwah. Selama ini hal itu tidak ada. Hanya keyakinan semu bahwa “tidak mungkin ustadz atau da’i itu maruk sama uang”. Dalam hal masalah uang pun (honor da’i) jika ada pedoman standarisasi dakwah bisa diketahui pasti apakah boleh atau tidaknya dan bagaimana etikanya jika boleh. Hal ini pun tidak ada. Semua hanya berdasarkan “Manajemen Qalbu”, manajemen seenaknya hati saja.**[harja saputra]